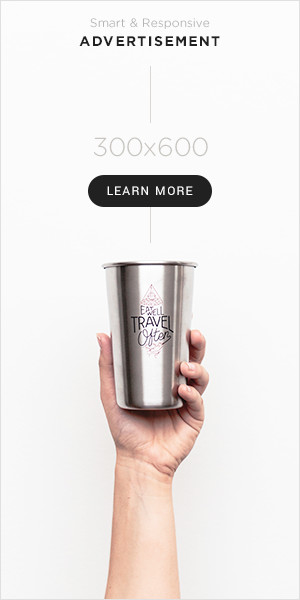Ini adalah artikel review dari komunitas Cinemags dan tidak mencerminkan pandangan editorial Cinemags. Andapun bisa membuat artikel serupa di sini.
![]()
Profesor dambaan pria dan wanita, Robert Langdon, kembali lagi dalam petualangan berdarah berlatar sejarah. Setelah mengutak-atik formalitas Gereja dengan “Angel & Demon”, bermain dengan doktrin Kristianitas lewat “Da Vinci Code”, serta bermabuk-mabuk semiotika esotrik melalui “The Lost Symbol”, novelis kawakan Dan Brown mencoba kembali menelusuri Eropa Abad Pertengahan melalui sastra gerejawi legendaris, “The Divine Comedy” karya Dante Alighieri.
Seperti biasa, novel-novel laris Dan Brown pun pasti menggoda untuk difilmkan. Dengan melewati “The Lost Symbol” yang menurut studio bakal mirip ceritanya dengan “National Treasure”, Sony Picture langsung memfilmkan “Inferno”, yang judulnya diambil dari salah satu segmen Divine Comedy. Film berdurasi 2 jam ini masih disutradarai oleh Ron Howard, dan dibintangi oleh “American Sweetheart” Tuan Tom Hanks sebagai Robert Langdon.
“Inferno” secara garis besar menceritakan Prof. Langdon yang (seperti biasa) terjebak dalam masalah, organisasi rahasia, aparat, dan wanita. Kali ini, ada profesor maniak bernama Bertrand Zobrist (diperankan Ben Foster), pecinta Dante yang menafsirkan “The Inferno” sebagai wacana tentang penghukuman umat manusia. Manusia dianggapnya sudah terlalu banyak beranak-pinak di muka Bumi, karena itu, perlu ada pengurangan besar. Untuk merealisasikannya, dia menciptakan virus penyakit yang diletakan di tempat rahasia. Pada waktu yang ditentukan virus itu akan meledak dan menulari semua manusia. Melalui virus tadi, visi Zobrist tentang “neraka dunia” ala Inferno akan tergenapi. Prof. Langdon, dengan kharisma intelektualnya, (seperti biasa lagi) berusaha menghentikan tindakan Zobrist dengan bantuan wanita prodigy Sienna (diperankan oleh Felicity Jones), WHO, dan organisasi intelijen misterius. Lagi-lagi seperti biasa, ada intrik dan konspirasi tak terduga yang mengungkap kepentingan2 rahasia diantara mereka.
Boleh saja kita mengatakan apapun soal Dan Brown dan karyanya, mulai dari “sastra pop pretensius” hingga “psuedo intellectual”. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pria kelahiran New Hampshire ini adalah pencerita yang ulung. Booming “Da Vinci Code” 10 tahun lalu membuka genre baru dalam sastra populer, Genre Konspirasi. Gaya penulisannya mengalir dan thrilling. Ditambah dengan sisipan sejarah dan quasi-okultisme yang memukau, membuat pembaca selalu ingin tahu sampai halaman terakhir. Selain itu, ciri khas Brown adalah seringkali menggunakan sudut pandang benak para tokoh ceritanya yang berbicara dalam hati. Faktor inilah yang membuat upaya memfilmkan novel-novel Dan Brown adalah tantangan tersendiri. Saya pribadi tidak pernah lebih dari 5 hari membaca novelnya. Rekor saya adalah “Inferno” yang saya habiskan dalam waktu 2 hari. Novel “Inferno” bagi saya, walaupun tidak sekontroversial seri Robert Langdon sebelumnya, adalah karya paling kelam dan angker dari keempat novel lainnya. Lalu bagaimana dengan filmnya?
Pertama dari sisi pemeran. Sehebat apapun seorang Tom Hanks, beliau sudah terlihat amat tua untuk ukuran Prof. Langdon. Untuk kesinambungan (dengan asumsi Dan Brown masih betah menulis seri ini), lebih baik cari aktor pengganti lain yang lebih muda untuk film kedepannya. Saat membaca “Inferno” entah mengapa di kepala saya sudah terpatri sosok Diane Lane untuk memerankan Elizabeth Sinskey, direktur WHO. Walau dalam eksekusinya pihak studio memakai aktris Denmark Sidse Babett Knudsen. Untuk pemeran Sienna Brooks, saya senang saja saat si gigi kelinci lucu Felicity Jones didapuk memainkannya. Saya juga senang melihat aktor India Irffan Khan dan aktor Perancis Omar Sy semakin diperhitungkan Holliwud.
Aspek sinematografi dan musik latar juga tiada masalah. Khusus Hans Zimmer, beliau tampaknya lagi doyan bermain sound elektrik. Setelah kenyang ber-dubstep dengan Junkie XL, komponis Jerman ini sepertinya mulai kena racun Daft Punk.
Namun ada dua hal penting yang benar-benar mengganggu saya di film “Inferno”. Pertama, naskah. Kedua, imajinasi visual sutradara Ron Howard. Saya pribadi sebenarnya tidak masalah jika ending film ini tidak menuruti ending di novelnya (yang memang mencengangkan). Namun setidaknya naskah garapan David Koepp haruslah tetap menangkap esensi novelnya. “Inferno” dalam novelnya secara muram menggambarkan bagaimana Wabah Hitam yang melanda Eropa pada abad 12-13 benar-benar meninggalkan trauma mendalam bagi peradaban Abad Pertengahan. Puluhan juta orang meninggal. Dan bagi Eropa Kristen, itulah untuk pertama kalinya mereka mempertanyakan esensi tentang keberadaan Tuhan yang maha pengasih. Bagi mereka Tuhan menghukum mereka dan sebagai antitesi dari Maha Pengasih, hadirlah Neraka dalam bentuk wabah penyakit. Wabah Hitam-lah yang akhirnya menjadi inspirasi Dante Alighieri dalam menulis “The Divine Comedy” dimana dalam segmen “Inferno” digambarkan dengan gamblang seperti apa siksaan neraka dan para manusia nista yang dihukum disitu. Untuk sekedar diketahui, narasi dan gambaran dalam syair “Inferno”-lah yang menginspirasi gambaran modern dan ilustrasi hukuman neraka yang menghiasi imajinasi alam pikir Yudeo-Christian/Samawi saat ini.
Namun dimata antagonis utama Bertrand Zobrist, “Inferno” adalah inspirasi bagi penghukuman yang menciptakan peradaban baru. Wabah Hitam dalam sejarahnya memang menjadi salah satu pemicu terjadinya Rennaisance (Kelahiran Kembali) Peradaban Eropa. Dan sosok Zobrist digambarkan akan merekreasi Wabah Hitam versinya sendiri.
Dalam versi novelnya, semua elemen tadi dinarasikan dengan gelap dan mood yang pesimistik. Sangat mencekam. Namun entah kenapa versi filmnya kurang sukses mengangkatnya. Yang diangkat malah sisi asmara antara Prof. Langdon dan Dr. Sinskey serta …. (spoiler!) Kekurangan ini ditambah dengan Ron Howard yang amat minim menggunakan teknik supra-narasi visual yang seolah menjadi trademarknya seperti “The Beautiful Mind” dan “Da Vinci Code”. Saya membayangkan ada supra-narasi yang memperlihatkan lebih sering kejadian Eropa saat Wabah Hitam, lengkap dengan Topeng Paruh yang legendaris dan traumatik saat Prof. Landon menjelaskan soal latar belakang Divine Comedia. Namun Tuan Foster mungkin sedang malas atau studionya pelit kasih bujet tambahan. Film ini malah terlalu berfokus pada aksi. Kalau soal film aksi bertema seleksi manusia ala Nabi Nuh, film “Kingsman” saja sudah lebih dari cukup.
Pada akhirnya, “Inferno” agak jauh dari ekspetasi saya tentang adaptasi yang angker dan kelam. Bagi pembaca novelnya, pasti amat kecewa. Bagi yang belum membaca, “Inferno” tetap layak jadi hiburan. Film adaptasi Prof. Langdon sebelumnya seperti “Da Vinci Code” memang tidak luar biasa. Namun saya masih terkesan dengan upaya visual Ron Howard yang mengrekreasi supra-narasi adegan2 historis macam Konsili Nicea, pembakaran Templar, penghancuran patung pagan oleh Romawi Kristen, hingga solusi Appel dan Isaac Newton yang masih membuat saya terpesona. Akhir kata, “Inferno” adalah adaptasi yang generik dan malas. Tetap layak tonton, tapi malas.