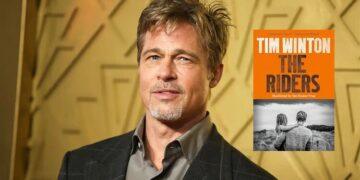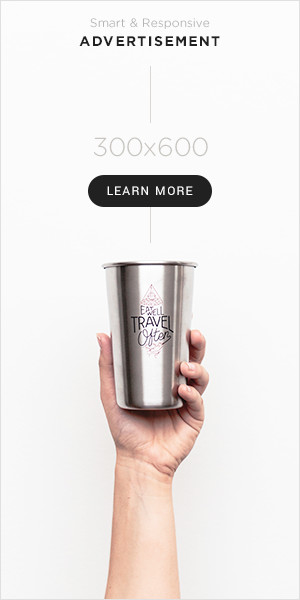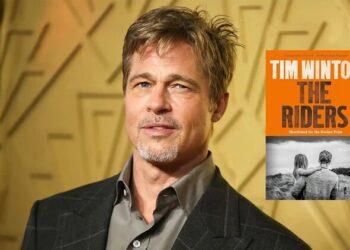Obviously a movie doesn’t smell like anything, but Tykwer manages to make us smell things uses sight for smell.
Sama seperti teknologi di bidang lainnya, teknologi perfilman juga seiring waktu berubahnya zaman berkembang dengan pesat. Ambil contoh, teknologi 3D yang kini seakan-akan menjadi andalan banyak studio Hollywood untuk mengeruk keuntungan melalui sajian yang memanjakan mata. Dan, desas-desusnya bahkan kini mulai menuju ke arah format 4D, yang sudah dirintis oleh sekuel paling gres Spy Kids. Bukan tidak mungkin, nantinya dalam beberapa tahun ke depan, teknologi ini sudah banyak yang mengusung, di mana penonton film bisa turut mencium aroma yang muncul dari sajian film.

Namun, usut punya usut, ketika ‘memfilmkan aroma’ merupakan hal yang cenderung mustahil, ada sineas yang berani menghasilkan film yang berkisah tentang bebauan. Adalah sutradara muda Tom Tykwer lewat karya garapannya; Perfume: The Story of a Murderer, yang kisahnya diangkat dari kisah novel berjudul sama karya Patrick Suskind yang pertama kali dipublikasikan perdana pada tahun 1985. Perfume berfokus pada Jean-Baptiste Grenouille; seorang murid peracik parfum di abad ke-18 Perancis, yang terlahir tanpa memiliki tubuh, dan terobsesi menciptakan parfum dengan “keharuman sempurna”. Caranya sendiri terbilang ekstrim, di mana dalam prosesnya ia menguntit dan menghabisi nyawa belasan gadis muda yang masih perawan.

Permasalahannya, kisah itu salah satu aspek utamanya adalah keharuman yang notabene tidak kasatmata dan hakikatnya sebuah film tidak menawarkan aroma apapun. Hal ini juga diamini oleh novelisnya sendiri dan mengklaim hanya sineas kawakan sekelas Stanley Kubrick atau Milos Forman saja yang bisa merealisasikannya. Bahkan, di kalangan insan Hollywood sendiri Perfume diakui sebagai materi yang sangat sulit difilmkan.

Lalu, bagaimana cara Tykwer menyiasatinya? Metodenya sendiri terbilang sederhana. Ditambah desakan jadwal syuting yang hanya sebentar, karena tanggal perilisan di Eropanya sudah telanjur dipublikasikan, alih-alih memanfaatkan efek CGI yang memakan banyak biaya, sineas pembesut Run Lola Run itu mengorkestrasikan timnya untuk lebih memforsir sinematografi dan penggunaan narator sehingga bisa menstimulus otak para penontonnya seakan-akan mencium langsung dan menghirup aroma berbagai hal yang ia ingin ia hadirkan.

Contohnya, untuk membuat penonton mencium bau busuk maupun amis, Tykwer menyorot tumpukan sampah maupun onggokan ikan busuk dalam durasi yang cukup panjang, sedangkan untuk sesuatu yang harum, ia menampilkan gambar-gambar yang indah, enak dilihat, atau wujud paras yang cantik. Sedangkan, untuk menjelaskan kehebatan indra penciuman Grenouille, Tykwer menyorot deretan benda secara bergantian, dan narator menjelaskan bahwa itu yang sedang dirasakan sang tokoh utama lewat indra penciumannya.

Hasilnya, dengan teknologi ‘ala kadarnya’ itu, meski raihan di Amerikanya sangat mengecewakan, film ini berhasil menuai sukses di Eropa. Respon yang diraih oleh film dengan tema yang sangat unik ini juga lumayan menggembirakan. Bahkan, tidak sedikit juga kalangan kritikus yang kemudian memilih film ini ke dalam daftar film terbaik favorit mereka dan memuji keberanian, serta kecerdasan sineas muda asal Jerman itu dalam mewujudkan hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin bisa dilakukan. Meski tidak sampai memuaskan seluruh kalangan, lewat Perfume, inovasi Tykwer bisa dibilang sebagai terobosan perfilman, di mana ia dinilai berhasil menyajikan keharuman ke wujud visual, suatu gebrakan yang belum pernah disajikan sineas legendaris sekalipun, bahkan hingga saat ini. Cerita novelnya yang sangat khas juga membuat film ini semakin sulit dicari tandingannya.