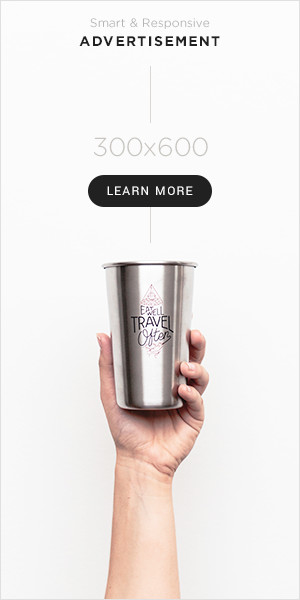Ini adalah debut Christian Rivers, seniman visual effect yang menjadi langganan Peter Jackson dalam menangani proyek visual Lord of The Rings, The Hobbit, dan King Kong. Penyertaan embel-embel nama Peter Jackson dalam trailer-nya merupakan bagian dari strategi marketing yang kemungkinan mengecoh ekspektasi audiens. Pasalnya film adaptasi ini memiliki potensi sukses besar sebagaimana halnya film-film Jackson yang lain, namun sayangnya masih jauh dari idealisme itu, malahan kurang memberi kesan mendalam. Bahkan Rotten Tomatoes hanya memberikan bintang satu setengah dengan kejamnya (lupakanlah Rotten Tomatoes ataupun IMDB), meskipun berbeda nasib dengan novelnya sendiri yang mendapat apresiasi baik, beberapa aspek dalam film ini tidaklah terlalu buruk.
Konsep post-apocalyptic memang bukan hal baru. Setingan, plot, dan para karakternya sedikit mengingatkan film-film adaptasi YA novel yang mengisahkan dunia distopia masa depan, (sebutlah Maze Runner, Hunger Games, etc) keunikannya ada pada nuansa steampunk yang kental, tema yang tidak biasa ditemui di Hollywood.
Berlatar peradaban mesin ribuan tahun ke depan, tidak diceritakan bagaimana sejarahnya kota London sang ‘adikuasa’ dibangun di atas roda yang digerakan mesin, yang pasti teknologi kita sekarang sudah di anggap purba, bahkan minion dan smartphone sudah menjadi barang museum. Atas dasar hukum “Municipal Darwinism”, Thaddeus Valentine (HugoWeaving) berambisi memburu kota-kota kecil. Ia adalah seorang politikus yang gila kekuasaan tapi tunduk kepada Lord Mayor of London, Magnus Crome. Valentine juga merupakan sasaran balas dendam si tokoh utama, Hester Shaw (Hera Hilmar) yang disinyalir puterinya sendiri. Ambisi Valentine yaitu menembakan senjata pemusnah masal ke lawannya, kota Shan Guo, rumah bagi kaum Anti-Tractionist. Keseluruhan narasi ini mengingatkan kepada Star Wars – versi steampunk dengan Anti-Tractionist sebagai kelompok rebellion.
Karakter pemeran utama (Hera Shaw) hanya menarik di awal-awal, dan selanjutnya tenggelam oleh karakter Valentine (Weaving memiliki karisma sekelas Nick Cave meskipun berperan antagonis), dan terlebih oleh tokoh CGI, Shrike (Stephen Lang). Pula peran heroine di film ini diambil alih wanita androginy, Anna Fang (Jihae) yang ridiculously selalu muncul bak malaikat penyelamat lengkap dengan kacamata hitam saat Hera Shaw dipepet bahaya. Di antara keseluruhan tokoh, Kedalaman karakter hanya dimiliki Shrike, sosok robot Frankenstein dengan masa lalu misterius. Sayangnya karakter motion capture ini tidak mendapat porsi lebih lanjut hingga akhir film, dan hanya meninggalkan rasa penasaran kepada audiens.
Kepiawaian visual sudah tidak bisa didustakan. Meskipun dibuat oleh teknologi CGI, tidak pernah dalam sejarahnya audiens dibawa menyaksikan onderdil mesin-mesin raksasa bekerja, memberikan mobilitas dan menghancurkan –merepresentasikan imajinasi steampunk yang awesome sekaligus mengerikan. View penonton juga dimainkan ke berbagai angle. Namun sayangnya lagi, kehebatan visual kurang didukung dengan kematangan plot. Terlalu banyak distraksi saat menontonnya, banyak adegan yang berpindah terlalu cepat sehingga tidak memberi audiens jeda untuk berefleksi, juga terdapat beberapa adegan kurang penting, seperti saat Robert Sheehan (Tom Natsworthy) sempat-sempatnya memilih jaket kulit sebelum lepas landas darurat.
Dengan menghiraukan berbagai kekurangan di atas, film epic adventure ini sekiranya masih terbilang fun bagi audiens remaja. Narasi sosial-politik, kekuasaan, senjata pemusnah masal, dan watak serta fitrah alami manusia; sebagai penghancur (direpresentasikan oleh sistem dan mesin) sekaligus pembawa damai (direpresentasikan oleh Anti-Tractionist yang memilih hidup di alam dengan figur menyerupai Dalai Lama sebagai pemimpin mereka) adalah topik menarik yang diceritakan kembali secara fiktif, seperti halnya dalam Star Wars dan LOTR, meskipun disuguhkan dengan kurang matang.