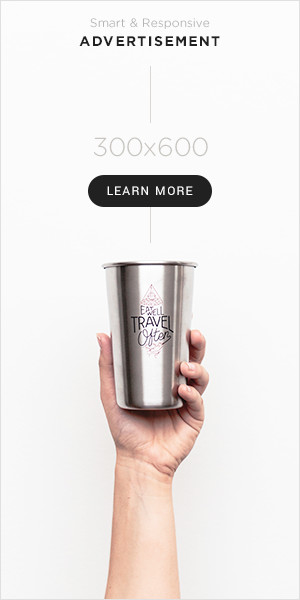Gerbong juara milik Alejandro Gonzalez Inarritu kembali masuk ke rel penantang bagi film-film “Oscarable”. Kali ini lewat “The Revenant” yang bercerita tentang pembalasan dendam yang konon disadur dari kisah nyata. Karya-karya dari sutradara Meksiko ini memang terkenal hampir selalu over the top (bahkan cenderung pretensius), khususnya secara artistik. Jika lewat “Birdman” Inarritu terus mengoyak syaraf rileks penonton dengan rentetan dialog yang seolah tanpa henti, “The Revenant” seolah mengambil cara berlawanan; Menyiksa lewat gambar.
Alasan utama saya menonton film ini di bioskop tentu saja untuk menyaksikan karya sinematografi dari Emmanuel Lubezki. Nama inilah yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan saya pada karya-karya dari sutradara Terrence Malick. Secara khusus, visual “The Revenant” sedikit banyak mengingatkan saya pada “A New World”-nya Malick yang sama-sama mengambil setting Amerika post-columbia lengkap dengan para Indian. Saya tidak perlu membahas divisi pemeran, karena duo Leo DiCaprio-Tom Hardy sudah cukup memberi garansi.
Dengan amunisi seganas tadi, sanggupkah The Revenant memuaskan harapan? Sayangnya, kurang. Semua pengambilan gambar di film ini memang diperhitungkan secara artistik, dengan ditunjang musik latar yang moody dan desain produksi yang renyah dan ultra detail. Namun sama seperti traktiran “all you can it“, terlalu banyak kenikmatan pun bisa membuat eneg. Saya beberapa kali menguap kantuk ketika terlalu sering dihujam gambar salju, badai salju, putih salju, sungai, kuda (dan bangkainya), pohon2 sub tropis, hingga musket dan ceceran darah. Belum lagi suhu ruangan bioskop yang cukup dingin. Kombinasi hal-hal tadi hampir membuat menyerah. Pilihannya adalah meninggalkan studio atau tidur. Kabur sebelum film selesai bukanlah gaya saya. Tertidur? Ya, mungkin ada sedetik atau sepuluh detik saya memejamkan mata (terlepas dari kondisi badan yang agak meriang). Akhirnya, saya tetap mengambil sikap seperti penikmat film bermartabat; menonton sampai habis, dengan segala siksaannya.
Tapi.
Saya mendadak sadar. Apa yang saya rasakan adalah apa yang seorang Glass (DiCaprio) mungkin rasakan. Setelah badannya koyak-moyak digasak beruang grizzly, Glass harus menerima kenyataan teman-temannya sesama pemburu kulit beruang meninggalkan dirinya. Belum cukup, Fitzgerald (Tom Hardy), salah satu anggota yang tamak, membunuh satu-satunya putra Glass. Dengan kehancuran fisik dan mental yang tak terkira dan juga disiksa oleh musim dingin sekaligus ancaman klan Indian jago panah yang mematikan, Glass terus berusaha mempertahankan nyala hidup. Apa yang menggerakkannya untuk terus bertahan? Naluri survival dan dendam kesumat. Namun di tengah-tengah segala determinasi tadi, tidak sedikit momen ketika Glass digoda oleh bayang-bayang almarhumah istrinya untuk menyerah dan merelakan. Mungkin saja dengan menyerah lalu “tertidur”, Glass bisa bertemu istri dan putranya lagi. Namun Glass tidak mengambil jalan termudah. Dia pun rela melakukan halhal yang membuat seorang John Rambo tidak ubahnya seperti anak Pramuka. Semua demi bertahan hidup. Semua demi menggenapkan kesumat.
Oleh karena itulah film ini HARUS ditonton di bioskop. Menonton di laptop atau home theatre rumah dengan segala teknologi skip-pause-rewind-fast-forward akan membuat anda kehilangan esensi film ini. Bagi yang tetap kuat iman tidak menonton bocoran dvd rip-nya hingga rilis resmi, selamat menikmati penyiksaan dari Tuan Innaritu.
Skor:8,7
Catatan Tambahan:
Ahh Leo, akting anda memang bagus. Tapi Leo tetaplah Leo yang suka mengerang dan memicingkan dahi. Saya sarankan Om Leo agar sekali-sekali main di genre komedi murni agar jangkauan ekspresinya lebih kaya. So, Oscar 2016 for Leo? saya sepakat. Tapi bukan karena aktingnya di sini (akting Tom Hardy sedikit lebih nampol). Cari saja alasan lain, entah kasihan atau mungkin wajahnya di film ini yang makin mirip Mark Walhberg.
![]()
Ini adalah artikel review dari komunitas Cinemags dan sama sekali tidak mencerminkan pandangan editorial Cinemags. Anda bisa membuat artikel serupa di sini.