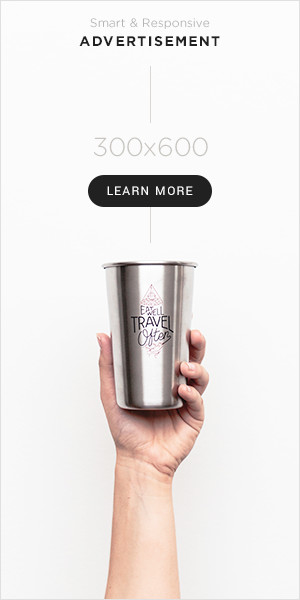Hype prarilis sering mengkonsumsi film sebelum resmi diputar di bioskop. Spekulasi trailer, rumor plot, dan prediksi musim penghargaan semuanya membantu mendorong industri film-jurnalisme. Tetapi, bahkan dengan tolok ukur itu, gelombang ketertarikan pada A Star Is Born, film drama musik yang menjadi debut aktor Bradley Cooper sebagai penulis dan sutradara serta dibintangi solois wanita kontroversial Lady Gaga, sangat menarik untuk dicermati.
Pasalnya, sangat jarang Hollywood menghasilkan sebuah foto “peristiwa” yang bukan tentang superhero atau Star Wars akhir-akhir ini — lebih jarang lagi, film seperti itu menjadi drama berat R-rated tentang alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba, sekaligus merupakan remake klasik dari zaman keemasan film.
Premis filmnya sebenarnya bukan kisah yang sama sekali baru: Seorang bintang musik besar bertemu dengan sosok berbakat yang tidak dikenal, mereka jatuh cinta. Lalu, situasi berbalik 180°, sang bintang mengalami problematika depresif yang membuat kariernya menukik tajam, sementara kekasihnya justru namanya meroket sebagai bintang baru. A Star is Born garapan Cooper ini merupakan kali keempat materi ini diangkat ke layar lebar. Bahkan, entah memang diinspirasi dari materi yang sama ataukah tidak, di ranah Bollywood juga ada film dengan premis mirip berjudul Aashiqui (1990) dan hasil remakenya, Aashiqui 2.
Jika ditelusuri satu persatu, hasil daur ulang A Star is Born sendiri dari film asli rilisan 1937nya, setiap kalinya menyuguhkan meta-narasi dan nasib yang berbeda-beda. Dalam versi 1954, dibintangi Judy Garland yang paling kentara adalah comeback besar mantan bintang cilik untuk dipandang sebagai aktris yang serius. Sementara, dari versi 1976, Barbra Streisand yang membintangi film ini malah seakan menjadi blunder bagi kariernya, karena saat itu namanya sudah terlalu kondang untuk bisa dipercaya sebagai “berlian belum terasah” yang baru diketemukan.
Lalu bagaimana dengan versi terbarunya ini? Untuk hal ini, jika mau dibandingkan situasinya, Lady Gaga berada tepat di tengah-tengah. Sungguhpun demikian, reputasinya sebagai pemusik unik menghadirkan daya tarik tersendiri, apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini sang diva cenderung tampil lebih kalem dan memperlihatkan kemampuan vokalnya (yang sebenarnya memang di atas rata-rata) daripada saat dirinya lebih dikenal karena sosok kontroversialnya.
“Tampilan baru” sang diva ini yang tampaknya dimanfaatkan secara jeli oleh Cooper sebagai amunisi apa yang ingin ia kedepankan di film garapannya ini. Karena harus diakui, dalam versinya ini, Cooper mengedepankan pada gagasan “keaslian” dalam musik, sebagaimana jalur yang sedang dijalani oleh Gaga. Aspek lain yang dikedepankan di versi ini namun belum dieksplorasi lebih mendalam di versi-versi sebelumnya adalah bagaimana aspek “keaslian” dalam musik ini dalam kaitannya dengan ketenaran yang diraih. Hasilnya, versi garapan Cooper ini kentara impresif karena eksplorasi penyutradaraannya yang begitu mendetail. Bahkan, aura ini sudah berhasil dibangun sejak menit pertama, lewat adegan Maine membuka konser. Berani taruhan, pasti banyak audiens yang merinding saat Cooper mulai menyanyikan tembang “Black Eyes” di depan ribuan penonton.
Cooper sendiri yang memainkan sosok pemusik bermasalah, sukses memberikan nyawa yang luar biasa. Tidak hanya mampu terlihat meyakinkan, audiens akan mudah melihat bagaimana karakternya merasakan kekhawatiran seorang bintang yang tengah berada di puncak terhadap kelangsungan ketenarannya.

Film versi Cooper ini lebih berhati-hati untuk memanusiakan pemeran utama pria, sekarang penyanyi country bernama Jackson Maine. Sejatinya, ini adalah pilihan yang mungkin terdengar kontraintuitif mengingat banyaknya kendaraan bintang pria dalam film, tetapi menonjolkan karakter adalah hal paling cerdas yang Cooper lakukan (yang menulis film dengan Eric Roth dan Will Fetters). Maine terasa seperti orang sungguhan, dan masalahnya terasa seperti masalah nyata, bukan simbol sesuatu yang lebih besar. Ini membuat keputusan Ally (Gaga) membuang banyak hal dengan Maine jauh lebih masuk akal, terutama karena ia mulai menurun; nasib mereka terasa terjalin lebih dari sekadar tujuan plot sederhana.
Ally masih, tentu saja, tokoh utama film tersebut. Lady Gaga dan lagu-lagu Ally (ditulis oleh Gaga dan yang lainnya) menjadi pusat perhatian. Tetapi kemenangan film terletak pada kemampuan Cooper untuk menikmati romantisme semata — untuk hubungan di pusatnya dan untuk tindakan kreativitas itu sendiri. Adegan film Jackson dan Ally yang menulis dan membawakan lagu adalah yang paling menegangkan; ketegangan kunci duo dalam tindakan akhir yang lebih gelap berkisar pada gagasan, dan definisi, tentang “penjualan.”
Dari hasil akhir besutannya, mudah dilihat bahwa Bradley Cooper telah menorehkan pencapaian debut luar biasa yang hasilnya setara kaliber sineas veteran. Solid dari segi cerita dan apik dalam membangun chemistry, Apa yang dihadirkan A Star is Born 2018 terasa real dengan kehidupan nyata. Sebuah film megahit dewasa klasik, yang sulit dijumpai sekarang ini, namun mudah diterima dan ceritanya mengena bagi audiens masa kini. Sekaligus menghidupkan kembali gairah ketertarikan pada genre drama romantis, genre yang kini tengah meredup dan jumlahnya berkurang di era maraknya film-film superhero sebagai penguasa panggung Hollywood.