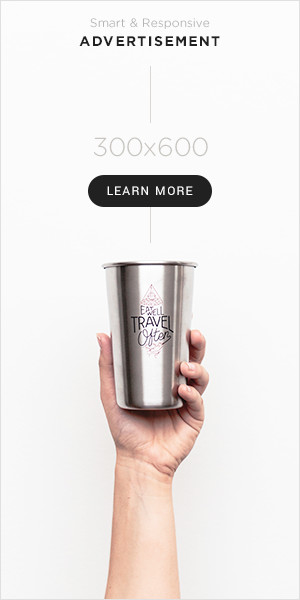Sejak kelahirannya di Jepang sekitar 7 dekade lalu, King-Kong dan Godzilla tidak bisa dipisahkan, kedua makhluk fiktif tersebut berkembang menjadi waralaba yang tidak ada matinya. Ratusan remake, sekuel, komik, video games King-Kong/ Godzilla turut meramaikan pop kultur dari generasi ke generasi.
Meskipun remake Godzilla telah muncul beberapa dekade lalu di Hollywood, namun generasi millenial mungkin mengingat film Godzilla terpopuler yang dirilis TriStar tahun 1998. Kemudian di tahun 2014, WB dan Legendary merilis reboot Godzilla di bawah komando Gareth Edwards yang berakhir meraup untung sebesar $529.1 juta. Berangkat dari kesuksesan tersebut, Edwards telah memikirkan sekuel Godzilla selanjutnya meskipun dalam prosesnya, penyutradaraan jatuh ke tangan Michael Dougherty.
Sekuel ini merupakan lanjutan dalam MonsterVerse Kong: Skull Island (2017) sekaligus berpatok pada Godzilla (2014) yang menuai kritik positif di segi drama dan pengkarakteran, namun dikeluhkan karena kurangnya porsi adegan menyangkut reptil raksasa tersebut. Keluhan ini dijawab Dougherty secara drastis dengan menaruh sebanyak lebih dari tiga monster raksasa ke dalam filmnya. Plotnya sendiri melibatkan kembali para monster populer produksi studio Toho (Ghidorah, Rodan, Mothra, dan King Kong).
Bagi para penggemar berat, seharusnya pertarungan para monster-monster prasejarah, Mothra, King Ghidorah, Rodan, menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi bagi yang ingin lebih dari sekedar aksi perang antar monster, mungkin akan terasa ada yang kurang dari tontonan ini.
Pertama-tama harus diakui bahwa ceritanya tidak sebagus ekspektasi kemegahan trailer-nya. Jika hanya berekspektasi pada visual menakjubkan, pertarungan dasyat, kemenangan Godzilla, dan apocalypse umat manusia, maka hal itu telah terpenuhi dengan semestinya, namun untuk urusan kedalaman karakter dan jalan cerita, agaknya cenderung membingungkan dan membosankan.
Sementara Millie Bobby Brown, Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Bradley Whitford memerankan karakter mereka dengan baik, maka Mark Russell dan Vera Farmiga kurang memberikan chemistry untuk karakter yang mereka perankan.
Menghiraukan kicauan kritikus mengenai terlalu kerasnya gaung aksi gontok-gontokan monster dan minimnya drama, sejatinya inilah tradisi film bertema Kaiju; mengutamakan adu jotos para monster raksasa dan menipiskan porsi drama.
Pesan yang diangkat sebenarnya juga cukup menarik dan kontroversial, kembali mengingatkan bahwa populasi umat manusia yang semakin bertambah memenuhi bumi merugikan spesies lain.
Pandangan ini diyakini oleh Jonah (Charles Dance), mantan veteran Inggris yang banting setir menjadi seorang eco-terrorist, ia percaya bahwa keserakahan manusia menjadi penyebab kepunahan mereka sendiri dalam andilnya menciptakan perang, dan polusi. Alhasil monster-monster ini datang sebagai hukuman atas dosa manusia. Pandangan tokoh antagonis ini tidak bisa dibilang salah, ia pun menjalankan misi main hakimnya sendiri; mengembalikan keseimbangan alam, menipiskan sebagian populasi untuk mencegah terjadinya kepunahan, dengan membuka kotak pandora (Titans), dan Emma sepakat akan hal itu.
Di akhir kredit film ditampilkan bagaimana kondisi bumi dan spesies lain lebih lestari seiring kebangkitan para Titans di beberapa titik penjuru dunia serta menipisnya populasi manusia, juga ditampilkan gambar- gambar makhluk purba dari artifak sejarah, serta buku-buku mitologi yang menggambarkan kraken dan Dinosaurus, seakan kebangkitan para Titans menandakan kembalinya kondisi pra-sejarah dan era baru. Penggambaran tersebut merupakan fantasi yang bagus, walaupun terdengar mengada-ngada.