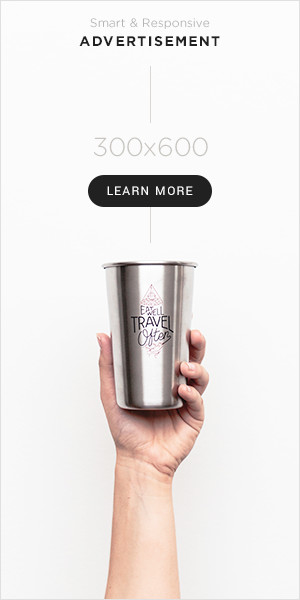Film terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2015 ini bagi saya adalah film yang sederhana. Sesuai judulnya, “Siti” bercerita tentang sosok Siti yang galau gundah gulana dikelilingi kemiskinan, jeratan utang, dan sang suami yang lumpuh layu. Konfliknya pun jauh dari rumit dan mungkin sudah klise, yaitu dilema antara moral dan realitas. Antara pasrah menerima “takdir” atau berkehendak bebas.
Hal utama yang membuat “Siti” menjadi istimewa adalah usaha sang sutradara, Eddie Cahyono, untuk menjadikan film ini efektif dan praktis, namun tetap estetis. Pertama, skup film tidak pernah keluar dari sosok Siti (diperankan aktris pendatang baru Sekar Sari). Dia muncul di setiap adegan, mulai dari mengejar anak lanang semata wayangnya yang malas mandi, menjual rempeyek di pantai Parangtritis, hingga mabuk oplosan melayani tamu di karaoke kelas kampung.
Kedua, dari sisi sinematik. Film berbujet 150 juta ini mengambil gambar dengan teknik hitam putih. Teknik semacam ini sudah jamak di dunia sinema, namun jarang digunakan sineas lokal. Saya tidak tahu apa motivasi utama sang Sutradara menggunakan B/W. Bagi saya pribadi, penggunaan warna yang minimalis-monokromatik akan mereduksi cukup banyak informasi dan impresi visual. Konsekuensinya, penonton akan lebih terfokus pada gerak dan mimik para pemeran. Untungnya seksi perwatakan tampil mumpuni. Akting setiap pemeran tidak terlihat terlalu dibuat-buat. Baik dari gestur, aksen (Jawa-Jogja), maupun ekspresi terlihat dan terdengar renyah, bahkan seringkali menyelipkan unsur komedi yang memancing gelak tawa. Penonjolan unsur perwatakan tadi juga semakin ditekankan dengan teknik pengambilan gambar tanpa jeda (long shot) yang menguasai lebih dari 60% film.
Ketiga, “Siti” sepertinya tidak dibuat untuk menggurui. Tidak ada adegan meraung-raung dan histeris. Tidak ada adegan berdoa sambil berlinang air mata meminta perubahan nasib. “Pesan & moral” dari film yang 95% dialognya menggunakan bahasa Jawa ini tidak ditampilkan secara eksplisit. Pergumulan Siti pada akhirnya adalah pergumulan yang personal dan sunyi, khususnya ketika dia mulai membandingkan suaminya yang disfungsi dengan sosok polisi gagah (dan berkumis) bernama Gatot.
Diluar hal-hal di atas, “Siti” tetap dibungkus dengan kemasan audio-visual yang layak tonton. Untuk tata suara, sudah cukup pas dan tidak bocor. Untuk sinematografi, teknik hitam-putih tidak menjadi penghalang untuk menciptakan komposisi gambar yang artistik. Saya senang pada adegan transisi yang mengambil lansekap laut, ombak, pantai, dan matahari terbenam di horizon. Komposisi visual tadi semakin diperkuat dengan tata musik yang digubah oleh Krisna Purna. Pemilihan alat gesek tradisional rebab sebagai instrumen utama cukup efektif menciptakan kesan getir, mistis, dan menyayat. Selain rebab, piano juga digunakan pada bagian2 akhir film.
Akhir kata, “Siti” sekali lagi adalah sajian sinematik yang efektif dan minimalis berbalut unsur lokalitas yang bukan sekedar tempelan. Karya yang wajar namun tetap berpuitik. Kesederhana-wajaran inilah yang membuat pesan dan tujuan film ini tersampaikan. Eddie Cahyono (yang juga merangkap sebagai penulis naskah) tidak menggiring penonton ke sebuah ujung, melainkan menuju pantai yang luas bebas tanpa batas. “Siti” pada akhirnya adalah tentang Siti yang mempertahankan hidup.
Oh ya sekedar tambahan, bukan bermaksud untuk ber-jinggoisme. Film ini harus berkeliling di festival-festival terlebih dahulu sebelum menembus jaringan bioskop mainstream. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan untuk men-support langsung. Bukan karena faktor kasihan, namun karena film ini memang berkualitas. Apalagi jika anda penikmat drama.
Ini adalah artikel review dari komunitas Cinemags dan sama sekali tidak mencerminkan pandangan editorial Cinemags. Anda bisa membuat artikel serupa di sini.