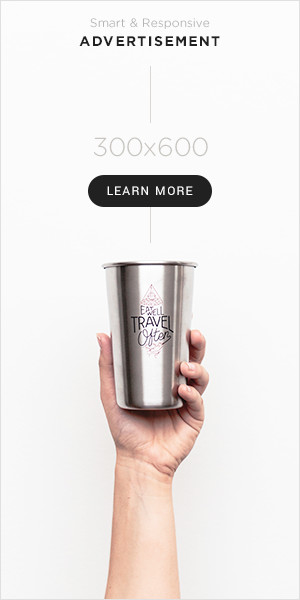Kasus pembantaian brutal merupakan suatu hal yang sudah lazim terjadi, namun horror yang menimpa Sharon Tate dan tiga orang temannya pada malam naas di 10066 Cielo Drive lebih diistimewakan di sejarah perfilman. Fenomena yang pernah mengguncang Hollywood di tahun 1969 itu terus menerus dibuatkan dokumentasinya dan difilmkan dengan kebanyakan memfokuskan pada sosok psikopat karismatik dan enigmatik ini.
Entah kebetulan atau disengaja, sejak kematian pemimpin kultus ini di 2017, demam Manson kembali populer di ranah perfilman. Buktinya, ada empat film yang berkaitan dengan Charles Manson dirilis di tahun 2019, dan Once Upon a Time in Hollywood adalah salah satu di antaranya. Sedangkan, tiga judul lainnya adalah The Haunting of Sharon Tate, Charlie Says, Tate, dan Once Upon a Time … in Hollywood, setelah setahun sebelumnya, film dokumenter bertajuk Inside The Manson Cult: The Lost Tape ditayangkan di televisi FOX.
Film-film mengenai Manson, karena saking banyaknya, mungkin malah menjadi membosankan dan gampang ditebak, namun, tidak untuk yang satu ini. Karena, khusus Once Upon a Time … in Hollywood, ini menjadi penuangan kisah berkaitan dengan tokoh fenomenal itu yang paling menarik. Pasalnya, ini adalah karya penyutradaraan kesembilan Quentin Tarantino. Dan, sudah tentu jika berbicara mengenai film-film QT, kewajaran dan kenormalan merupakan istilah yang harus disingkirkan jauh-jauh dari benak sebelum menyimak hasil garapannya.
Hal ini dikarenakan, menyaksikan film-film arahan sineas Quentin Tarantino menghadirkan kenikmatan menonton tersendiri. Pasalnya, Q.T dikenal sebagai seorang sutradara eksentrik yang sangat mencintai film dan memiliki bahan referensi teramat luar biasa. Ia juga adalah sosok yang tidak ragu menempuh resiko serta mencampuradukkan atau menabrakkan genre sebuah film dengan genre lain yang terkadang bedanya kontras satu sama lain. Hasilnya, film-film karya besutannya selalu ‘kaya rasa’ dalam artian yang sesungguhnya. Tidak hanya berhenti di situ, umumnya karya-karya penyutradaraannya juga dibangun dengan skrip berkualitas, yang membuat kalangan kritikus maupun insan perfilman kerap angkat topi padanya, serta membuat film-film arahannya selalu dinanti para penikmat film.
 Dengan setting Hollywood, Los Angeles tahun 1969, Rick Dalton adalah seorang aktor aksi veteran yang seiring waktu mulai menyadari bahwa kebintangannya makin meredup di tengah persaingan Hollywood yang sangat keras. Beruntung sang aktor punya pendamping setia, Cliff Booth, stunt doublenya yang selalu siap pasang badan baik di depan maupun balik layar untuknya.
Dengan setting Hollywood, Los Angeles tahun 1969, Rick Dalton adalah seorang aktor aksi veteran yang seiring waktu mulai menyadari bahwa kebintangannya makin meredup di tengah persaingan Hollywood yang sangat keras. Beruntung sang aktor punya pendamping setia, Cliff Booth, stunt doublenya yang selalu siap pasang badan baik di depan maupun balik layar untuknya.
Bermukim di Cielo Drive, Dalton bertetangga dengan sutradara Roman Polanski dan pasangannya, aktris muda yang kariernya tengah menanjak, Sharon Tate. Sementara, saat menjalani aktivitasnya, dalam sebuah kesempatan Booth berkenalan dengan seorang gadis Hippie bernama Pussycat yang belakangan diketahui merupakan pengikut komunitas yang dipimpin seorang karismatik bernama Charlie Manson. Awalnya, tidak saling bersinggungan, perjalanan nasib kemudian saling menautkan mereka dalam peristiwa yang terjadi di malam 8 Agustus 1969.
Seperti sudah disinggung di atas, menikmati film besutan Tarantino akan merasakan keasyikkan tersendiri. Dengan catatan, akan lebih terasa impactnya jika sebelumnya sudah familier pada besutan- besutan terdahulunya. Meski, masih terbuka lebar pula bagi yang awalnya virgin dengan karyanya untuk juga bisa menikmatinya. Hal ini dikarenakan gaya storytelling Tarantino yang unik membuat film-filmnya bukan sajian untuk semua kalangan. Namun, bagi yang bisa memaklumi dan tidak bermasalah dengan itu, ganjarannya adalah pengalaman magis sinematik yang sulit dicari padanannya. Dan, hal itu pula yang dirasakan penulis setelah menyaksikan film ini.
 Mendekati garis finis sepak terjang penyutradaraannya (Tarantino pernah mengungkapkan hanya akan menyutradarai total sepuluh film saja), sang sineas sepertinya semakin menjadi-jadi. Apalagi, di sini, sang sineas memegang kendali penuh dan tidak dibatasi untuk menuangkan kreativitasnya. Hasilnya memang kentara sangat terlihat. Di sini, seakan – akan QT memberikan materi masterclass tingkat lanjut mengenai perfilman bagi para fansnya.
Mendekati garis finis sepak terjang penyutradaraannya (Tarantino pernah mengungkapkan hanya akan menyutradarai total sepuluh film saja), sang sineas sepertinya semakin menjadi-jadi. Apalagi, di sini, sang sineas memegang kendali penuh dan tidak dibatasi untuk menuangkan kreativitasnya. Hasilnya memang kentara sangat terlihat. Di sini, seakan – akan QT memberikan materi masterclass tingkat lanjut mengenai perfilman bagi para fansnya.
Bisa dibilang sebagai surat cinta sang sineas pada Hollywood, agak berbeda dengan tiga penyutradaraan terakhirnya, yang sangat menitikberatkan pada penataan skrip dan alur storytelling solid dengan gaya penuangan novel, karateristik itu tidak dijumpai di sini. Malah sebaliknya, meski ia punya skill storytelling di atas rata-rata, hal itu sepertinya sengaja tidak ia tonjolkan di sini.
Betapa tidak, QT seakan-akan tengah bersenang-senang dan mengeksplor dimensi bakat penyutradaraannya dengan sesuatu yang lain. Akibatnya, dari segi penceritaan, Once Upon a Time … in Hollywood mungkin bakal terasa membingungkan dan menyiksa penonton yang tidak siap dengan apa yang ingin disajikan sang sineas di sini. Jangankan untuk kalangan awam, bahkan bagi kalangan penonton film veteran sekalipun.
Namun, sebagai gantinya, QT menghadirkan eksplorasi yang luar biasa mengenai visual perfilman, baik itu meliputi detail setting, color palette, hingga pelbagai teknik pengambilan gambar. Filmnya juga memiliki perspektifnya sendiri, yang meski diinspirasi dari kejadian nyata, menegaskan posisinya sebagai karya fiksi.

Menyaksikan film ini akan menggali rasa nostalgia mengenai masa kejayaan film dan serial televisi di era 1960an melalui sepak terjang seorang aktor dan pemain penggantinya dengan pendekatan penuangan ala dokumenter. Namun, itu semua dieskalasi dengan performa prima akting kelas atas para pemainnya terutama tiga pemegang karakter pentingnya.
Aktor peraih Oscar Leo DiCaprio kembali menunjukkan kapasitas aktingnya sebagai aktor veteran yang pamor kariernya mulai menguap. Menampilkan sisi karismatik dan percaya diri di depan banyak orang namun di dalam diri rapuh pun emosional, DiCaprio dijamin akan kembali mampu memukau dan membius audiens. Sedangkan, Brad Pitt yang diserahi peran sebagai stuntman cool tampil meyakinkan. Baik Pitt dan DiCaprio juga mampu menciptakan chemistry memukau. Sangat menyenangkan melihat interaksi antara keduanya. Sementara, Margot Robbie yang memerankan sosok nyata, Sharon Tate, mampu mencuri perhatian dengan memerlihatkan sosok aktris muda yang periang dan selalu berpikiran positif.
 Tak pelak lagi, dengan gaya permainannya yang agak berbeda, sekali lagi QT memberikan sebuah film yang sangat berkelas. Tepat sasaran dalam menghadirkan perasaan nostalgia dengan referensi sangat tebal dari film, serial televisi, maupun budaya pop populer era 1960an. Sangat mudah untuk menyadari bagaimana dalamnya kecintaan sang sineas pada dunia film. Hampir setiap adegan yang dihadirkannya di sini setidaknya memiliki petunjuk penghormatannya pada Hollywood masa lampau.
Tak pelak lagi, dengan gaya permainannya yang agak berbeda, sekali lagi QT memberikan sebuah film yang sangat berkelas. Tepat sasaran dalam menghadirkan perasaan nostalgia dengan referensi sangat tebal dari film, serial televisi, maupun budaya pop populer era 1960an. Sangat mudah untuk menyadari bagaimana dalamnya kecintaan sang sineas pada dunia film. Hampir setiap adegan yang dihadirkannya di sini setidaknya memiliki petunjuk penghormatannya pada Hollywood masa lampau.
Walaupun sajiannya kali ini lebih beresiko dan rasanya bakal menantang intuisi para penontonnya lebih dari sebelum-sebelumnya, tetap saja Once Upon a Time … in Hollywood bukanlah film sembarangan. Malah justru sebaliknya, meski narasinya ibarat mengalir tidak tentu arah hingga terasa nyaris tanpa plot, dengan caranya sendiri QT mempertontonkan teknik superior membesut sebuah film, yang tetap saja hasilnya sangat menghibur, sangat memanja mata, namun juga unik dan berkualitas.