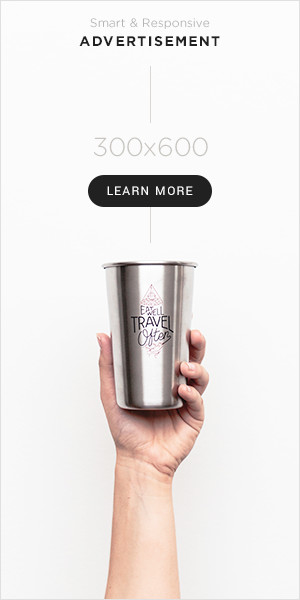Film berlatar perjuangan nasional kedua dari Garin Nugroho setelah “Soegija” (2012) ini bercerita tentang hidup-juang salah satu tokoh pioneer pergerakan modern Indonesia, Haji Oemar Said Tjokroaminoto (diperankan Reza Rahardian). Kisah dimulai dengan Tjokro kecil yang melihat penderitaan pekerja-pekerja perkebunan kapas yang dianiaya oleh mandor-mandor Belanda. Kegelisahan Tjokro terhadap keadaan juga diperlihatkannya di sekolah, dimana dia berani berdebat dengan guru Belanda totok. Sementara itu narasi-narasi agama Islam yang kuat tentang “hijrah” pada akhirnya berperan membentuk karakter dan kesadaran Tjokro terhadap posisi pribumi terhadap kolonial. Dan ketika beranjak dewasa, Tjokro pun mulai bertindak.
Era dimana Tjokroaminoto tumbuh besar adalah era fajar baru dimana politik etis Kolonial mulai melahirkan elit-elit pribumi yang “tercerahkan”. Tjokro adalah salah satunya. Selain itu, gagasan baru tentang nasionalisme dan pan-islamisme mulai bertumbuh di Hindia. Tjokro yang sedari awal sudah melihat potensi Islam Nusantara sebagai pemersatu lalu “hijrah” ke Surabaya. Di sanalah semua kisah perjuangan bermula. Dari bertemu Haji Samanhudi pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI), mengumpulkan pengikut, mengubah “Sarekat Dagang Islam” menjadi “Sarekat Islam (SI)”, mengganti blangkon dengan peci, hingga bersama pengikutnya menentukan arah perjuangan.
Judul “Guru Bangsa” sendiri bisa dijabarkan secara harafiah. Rumah Tjokro bersama istrinya di Gang Paneleh Surabaya seolah menjadi inkubator bagi calon-calon tokoh perjuangan bangsa kedepan. Mulai dari Agus Salim muda, Semaoen, Dharsono, Musso, hingga Kusno (Soekarno) yang masih culun namun antusias. Gagasan-gagasan baru selain pan-islamisme-nya Tjokro juga mulai berbenih. Terinspirasi dari Revolusi Bolshevik Russia, Semaoen dan kawan-kawan mencoba mengubah arah SI menjadi lebih revolusioner dan radikal. Sejarah mencatatnya sebagai “SI Merah” yang berfokus pada perjuangan kelas-kelas pekerja pribumi yang tertindas untuk merebut haknya.
Saya pikir Garin tidak mengharapkan film ini menjadi terlalu detail dan “mirip plek” aslinya, dengan segala intrik-intrik politiknya. Pendekatan Garin bahkan bagi saya sedikit teatrikal (dalam arti positif). Selain lakon-lakon utama, adegan para kawula-jelata dan tokoh-tokoh semi-fiksi juga banyak porsinya. Juga termasuk kehadiran tokoh simbolis seperti Bagong. Adegan-adegan jelata tadi menunjukkan bahwa sejarah bukanlah mirip kaum elit saja. Namun justru rakyat kecil lah yang merasakan langsung arah zaman mulai berubah. Mereka bahkan memandang kehadiran Tjokro dalam sudut pandang mesianik. Bahwa pada akhirnya di zaman mereka ada “Ratu Adil” pribumi asli yang akan membimbing dan merubah tatanan lama. Saat bertemu Tjokro mereka serta merta akan takzim dan mencium. Pada salah satu adegan seorang jelata pembuat kursi (dengan beskap dan dasi ala Barat) secara antusias dan mata berbinar berkata “sama rata-sama rata”.
Sebaliknya, adegan-adegan yang memperlihatkan kelambat-sadaran menanggapi arus zaman juga diperlihatkan, khususnya pada adegan mertua Tjokro sang Bupati Ponorogo (diperankan Sujiwo Tejo). Sosok sang Bupati mewakili gambaran elit priyayi pribumi pada masa itu yang umumnya cari aman karena sudah mendapat previlej jabatan dari pemerintah kolonial. Beberapa peran-peran juga mewakili keterkejutan dan apatisme dari masyarakat kecil menyaksikan dinamika di depan mata mereka. Semua diwakili dengan gumunan dan celotehan yang terasa spontan dan natural. Ada juga sosok Stella (Chelsea Islan) seorang Indo-Londo yang gamang dengan statusnya, apakah londo atau pribumi.
Secara khusus, Garin juga cukup “adil dan moderat” dalam merepresentasikan SI Merah. Mars Internationale, lagu pergerakan Komunisme sedunia, ditampilkan dalam gubahan Indonesia di beberapa adegan.
Sisi akting film ini bisa dibilang memuaskan. Reza Rahardian saya yakin dipilih selain karena akting, juga marketing. Namun sisi totalitas aktinglah yang lebih berbicara. Pemeran lain juga sudah pas. Seperti aktor-aktris senior macam Christine Hakim dan Didi Petet yang memerankan tokoh2 minor. Akting seorang Maia Estianti (cicit kandung Tjokroaminoto) juga cukup apik dengan logat suroboyoan dan nyanyian. Bahkan penampilan seorang Chelsea Islan membuktikan bahwa dia bukan sekedar Cinta Laura jilid 2.
Dari sisi teknikal dan artistik, “Guru Bangsa” juga sangat memanjakan mata dan telinga. Penggunaan tone dan kamera serta sinematografinya sangat indah. Dipadu dengan set artistik, kostum, dan, make-up yang detail, kesemuanya cukup berhasil menggambarkan kondisi Jawa awal abad 20. Tidak cukup lewat visual, musik latar juga cukup megah namun wajar. Tapi yang lebih impresif adalah gaya artistik Garin yang menampilkan lagu2 masa itu melalui mimik dan pengadeganan yang indah dan romantik. Gaya yang juga digunakannya dalam “Soegija”.
Kalau ada sedikit kelemahan, itu lebih ke sisi sumberdaya teknis. Saya bayangkan seandainya anggaran film historis macam begini diberi alokasi khusus nan layak pada divisi visual effect, pasti akan ada adegan Kota Surabaya atau Semarang tempo dulu secara lansekap dengan teknik CGI yang mumpuni dan indah. Sepanjang film ini memang sangat minim shot lansekap, kecuali di beberapa adegan seperti di pelabuhan dan kereta api. Dampaknya bagi saya adalah sedikit kelelahan visual karena shot-shot secara zoom in dan interior hampir dilakukan terus menerus. Tapi ini masih saya maklumi karena selain masalah anggaran, Garin juga berhasil menebusnya dengan hal-hal yang dijabarkan pada paragraf sebelum ini.
Akhir kata, kita yang telah merasakan dan “tenggelam” dalam kemerdekaan mungkin agak sulit untuk mengalami pikiran puluhan juta jelata Nusantara yang pada masa itu hanya bisa nrimo pada “takdir” ditindas oleh londo. Fase pikiran mereka mungkin hanya sampai sekedar “gelisah”. Lewat seorang “tercerahkan” seperti Tjokroaminoto-lah segala kegelisahan tadi bisa dimanifestasikan menjadi kesadaran massal akan sebuah “kemerdekaan”. Dan dengan meneladani epos Hijrah Nabi Muhammad, tindakan Tjokro pada akhirnya akan menjadi pemula epos modern sebuah bangsa yang akan “berhijrah”.
Garin Nugroho cukup berhasil menjadikannya sebagai sebuah film yang solid dan ambisius.
Catatan;
1) Walau secara garis besar mengangkat HOS Tjokroaminoto dan Sarekat Islam, film ini memiliki pesan kebangsaan yang universal. Jadi cocok untuk ditonton semua kalangan.
2) Jangan ragu untuk support langsung film ini! Dengan dukungan finansial dari kita (dengan membeli tiket atau DVD original), mungkin saja kedepannya film-film sejenis ini akan bisa diperkuat oleh banyak efek visual.
![]()
Ini adalah artikel review dari komunitas Cinemags dan telah disunting sesuai standar penulisan kami. Andapun bisa membuatnya di sini.